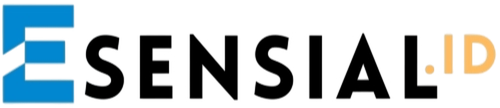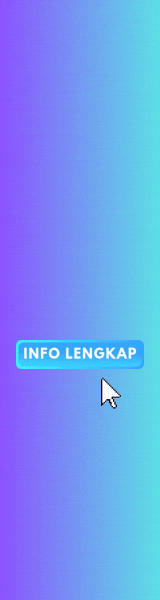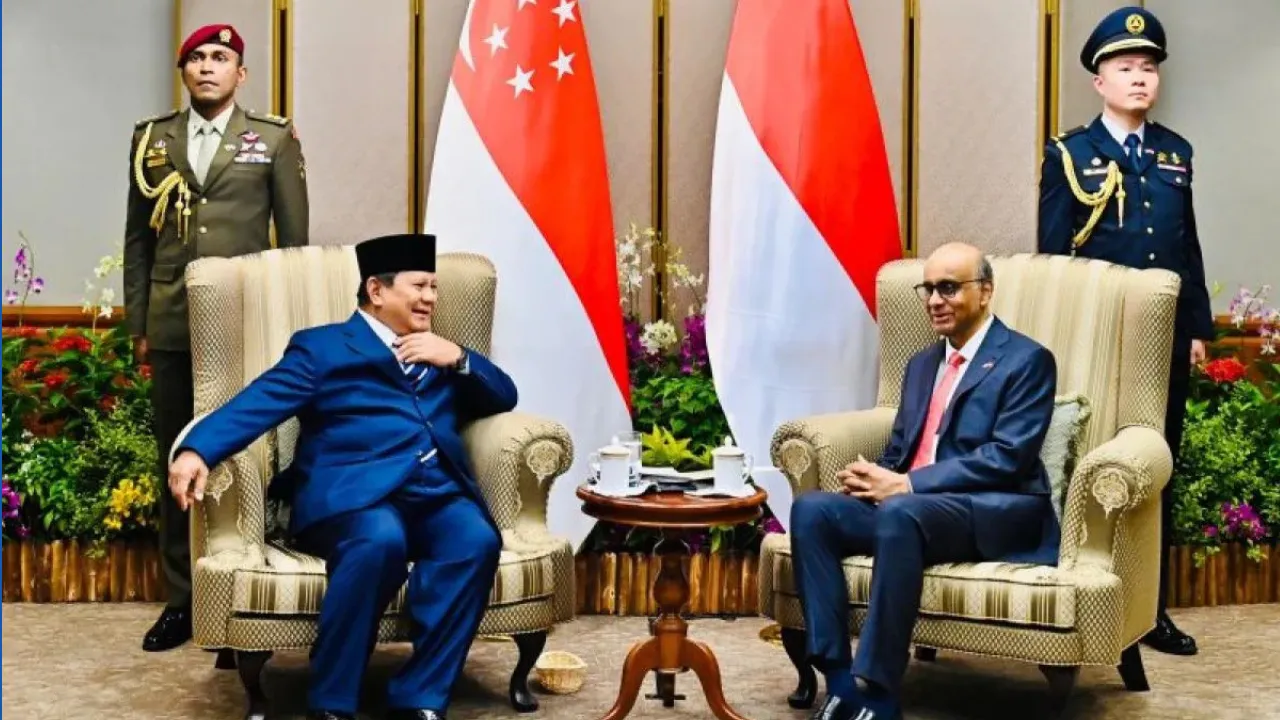Parlemen Thailand Dibubarkan di Tengah Ketegangan dengan Kamboja, Analis Khawatir Kekosongan Kekuasaan Picu Eskalasi Konflik

ESENSIAL NEWS – Keputusan Thailand membubarkan parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tengah meningkatnya ketegangan perbatasan dengan Kamboja memunculkan kekhawatiran serius di kalangan pengamat politik dan keamanan kawasan. Langkah ini dinilai berpotensi menciptakan kekosongan kekuasaan yang justru memperkuat sentimen nasionalisme domestik dan meningkatkan risiko eskalasi konflik yang hingga kini telah berlangsung selama enam hari tanpa tanda-tanda mereda. Situasi tersebut menjadi sorotan internasional karena terjadi bersamaan dengan meningkatnya aktivitas militer dan tekanan politik internal di Bangkok.
Pembubaran parlemen dilakukan oleh Perdana Menteri sementara Anutin Charnvirakul pada malam 11 Desember. Dalam pernyataannya, Anutin menyebut pemerintahannya sudah tidak lagi mampu menjalankan roda pemerintahan secara berkelanjutan, efektif, dan stabil di tengah tekanan politik domestik yang kian berat. Meski secara resmi diposisikan sebagai upaya “reset demokrasi”, keputusan tersebut segera memunculkan pertanyaan krusial mengenai siapa yang kini memegang kendali penuh atas kebijakan keamanan nasional Thailand, terutama saat konflik perbatasan dengan Kamboja sedang memanas, dilaporkan JawaPos dalam ulasan internasionalnya.
Pavin Chachavalpongpun, profesor di Centre for Southeast Asian Studies Universitas Kyoto, menilai pembubaran parlemen membuat posisi militer Thailand semakin kuat dan relatif tanpa pengawasan politik yang efektif. Menurutnya, angkatan bersenjata tetap beroperasi berdasarkan kerangka hukum yang ada, termasuk penerapan hukum darurat dan darurat militer di wilayah tertentu, yang memberi ruang diskresi sangat luas dalam operasi keamanan. “Dalam situasi pemerintahan sementara, keputusan jangka panjang praktis tidak bisa diambil,” ujar Pavin mengutip CambodiaNess. “Pilihan diplomasi menjadi terbatas, dan risiko bentrokan berlanjut meningkat karena tidak ada pihak yang memiliki mandat kuat untuk merundingkan penyelesaian permanen,” lanjut Pavin. Ia menegaskan dialog substansial baru mungkin dilakukan setelah terbentuk pemerintahan baru yang memiliki legitimasi penuh pasca pemilu.
Menurut Pavin, bentrokan terbaru di perbatasan telah memicu lonjakan nasionalisme di dalam negeri Thailand, disertai tekanan publik agar pemerintah bersikap lebih tegas terhadap Kamboja. Dengan pemilihan umum yang diperkirakan digelar dalam 45 hingga 60 hari ke depan, ia memperkirakan partai-partai politik akan mengadopsi retorika nasionalistik yang lebih tajam demi meraih dukungan pemilih. “Situasi seperti ini biasanya menguntungkan partai-partai berhaluan keamanan atau konservatif. Kelompok yang mendorong reformasi struktural justru sering diserang karena dianggap ragu-ragu. Pemilu cenderung memperkeras retorika nasionalisme, bukan meredamnya,” jelasnya.
Pandangan senada disampaikan analis geopolitik Seng Vanly yang menilai kegagalan Anutin mendorong reformasi konstitusi membuat pemilu dini tak terelakkan. Dalam kondisi tersebut, militer diperkirakan akan mengelola situasi perbatasan dengan keterlibatan sipil yang sangat terbatas. “Tanpa tekanan internasional yang terkoordinasi, krisis ini berpotensi memburuk,” kata Vanly.
Pebisnis dan pengamat politik Thailand, Arnaud Darc, juga melihat pembubaran parlemen sebagai cerminan masalah struktural yang lebih dalam dalam sistem politik Thailand. Menurutnya, pemerintahan Anutin kehilangan kemampuan untuk berfungsi secara efektif akibat tersendatnya amendemen konstitusi. “Anutin sejak awal bukanlah pemimpin eksekutif yang dominan, lebih berperan sebagai perdana menteri ‘penyeimbang’, yang menjaga relasi antara monarki, militer, Kementerian Dalam Negeri, jaringan daerah, dan parlemen yang terfragmentasi. Ketika satu pilar menarik dukungan, seluruh bangunan politik runtuh,” ujar Darc.
Darc menambahkan bahwa dinamika politik domestik Thailand sangat memengaruhi sikap negara itu terhadap Kamboja. Retorika publik kerap dipengaruhi monarki dan militer, sehingga sikap yang dianggap lunak menjadi risiko politik tersendiri. Di sisi lain, kalangan bisnis, masyarakat perbatasan, dan sebagian unsur militer justru menginginkan penahanan diri demi menjaga stabilitas, perdagangan lintas batas, serta menghindari sorotan internasional. “Hasilnya hampir selalu sama: pernyataan keras, pergerakan militer terbatas, diplomasi yang sangat hati-hati, dan tidak ada konsesi terbuka,” jelasnya.
Dari sisi Kamboja, Darc menilai Phnom Penh mengombinasikan penguatan posisi pertahanan, jalur diplomasi, dan pendekatan hukum internasional. Meski Perdana Menteri Hun Manet memimpin respons resmi, mantan PM Hun Sen disebut masih memengaruhi batas-batas strategis pengambilan keputusan. Menurut Darc, risiko terbesar justru terletak pada kesalahan membaca niat masing-masing pihak. “Kamboja menafsirkan ketegasan Thailand sebagai sinyal niat ofensif. Sebaliknya, Thailand bertindak terutama karena insentif politik domestik. Bahaya sesungguhnya bukan pada eskalasi yang disengaja, melainkan pada salah perhitungan struktural,” tandas Darc.